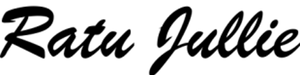Foto (featured image) ini saya temukan di galeri telepon genggam. Ada cerita di suatu akhir pekan bulan November 2022 itu.
Setelah anak lelaki bergabung dengan dua orang temannya untuk menonton film horor perdananya di bioskop, saya mencari tempat untuk makan siang.
Saya sendirian, karena suami masih di perjalanan pulang dari luar kota. Melihat jam tayang film, dari rumah sudah sempat terpikir bawa laptop untuk menulis, tetapi urung. Hari itu, lagi malas ribet bawa laptop. Gantinya, saya bawa buku bacaan dan notebook (loose leaf), plus pena. Tinggal gimana hati saja nanti: mau menulis atau membaca, sambil tunggu anak keluar bioskop.
Setelah makan, sempat berpikir: mau tetap di situ atau pindah ke tempat ngopi untuk menulis atau membaca. Akhirnya saya memutuskan pindah tempat ke foodcourt dan cari kopi. Kenapa di foodcourt? Ah… hanya karena areanya lebih terbuka dan lebih luas daripada coffee shop. Ya pokoknya cari suasana baru juga.
Saya hanya pesan Vietnam drip, lalu duduk di salah satu meja di foodcourt. Lihat jam, masih ada sekitar 45 – 50 menit sampai anak keluar dari bioskop.
Saya mengambil buku dan pena, untuk menuliskan ide yang muncul. Nanti di rumah, tinggal diketik ulang sekalian menyunting. Baru saja sekitar 2 menit buku dan pena berada di atas meja, datang seorang perempuan muda menghampiri saya.
“Maaf Bu, Ibu tinggal di Bandung?”
“Iya,” jawab saya.
“Maaf, mau mengganggu waktunya sebentar,” katanya langsung nyerocos. Saya lihat dia bawa brosur atau semacam berkas di tangannya.
Saat itu juga saya jawab.
“Aduh, maaf juga Mbak, saya sedang tidak ingin diganggu, saya mau menulis. Maaf ya…,” kata saya.
Si Mbak terlihat sedikit kecewa, tapi dia mengangguk dan segera berlalu.
Saat itu, memang itu yang ingin saya katakan. Pertama, saya menolaknya dengan intonasi dan cara yang baik. Kedua, saya menolaknya karena saya memang sedang ingin menulis, sementara waktu 45 – 50 menit sampai anak keluar bioskop adalah waktu yang relatif singkat buat saya rileks berpikir, merangkai kata dan menuliskannya. Ketiga, saya tahu persis bahwa saya sedang tidak membutuhkan apapun yang akan ditawarkan oleh seseorang, di hari itu. Justru dengan menolaknya, waktu saya dan dia sama-sama efektif. Saya bisa langsung menulis, dia bisa menawarkan “sesuatu” itu kepada orang lain.
Bisa bilang “tidak” kepada orang lain, sesuai kata hati saya, dulu-dulu adalah sebuah tantangan yang sangat susah saya keluarkan dari mulut apalagi jika permintaannya beralasan. Kenapa begitu? Biasanya takut mengecewakan orang lain, takut dianggap enggak baik, takut dianggap egois. Payah memang rasa enggak enakan ini.
Setelah tahu bahwa dampak dari beberapa “iya” untuk orang lain yang saya kabulkan ternyata menyiksa diri sendiri, saya mulai belajar bilang “tidak” (menolak) jika memang saya tidak mau, tidak sanggup, atau tidak bisa.
Risiko mengecewakan orang memang pasti ada, tetapi risiko sakit dalam hati lebih parah dampak jangka panjangnya. Pernah dan tahu banget rasanya mulut bilang “iya” yang sesungguhnya hati mau teriak “tidak”.
Jalan tengahnya ya membuat batasan, boundaries. Tentunya dengan cara sebaik mungkin (walau risiko orang lain kecewa tetap ada, namun itu sudah bukan ranah kita lagi), misalnya:
- Bisa, kalau hari ini sampai jam segini.
- Enggak bisa (dengan atau tanpa alasan)
- Oke, kerjaannya sampai mana? Saya sanggupnya segini.
- Wah maafkan, kalau begitu gak sanggup.
Insya Allah, kalau udah saling percaya dan paham, orang-orang yang dikasih batasan bakal mengerti dan gak bakal sakit hati. Saya pernah ditolak seseorang yang saya kenal baik, waktu mengajak dia gabung sebuah kegiatan. Buat saya dia keren bisa menolak dan saya pun menghargai pilihannya, sama sekali enggak sakit hati. Saya percaya dan paham bahwa dia memang bukan menolak saya, tetapi menolak kegiatan yang saya ajukan. Dan kami masih sering janjian ketemuan dalam keadaan baik banget.
Latihannya panjang dan masih berlanjut. Enggak mau kena jebakan orang yang memanfaatkan kebaikan, apalagi yang diiringi menghakimi baik atau tidak baiknya saya. Seperti sketsa yang pernah saya alami ini:
*) Masih teringat kata-kata seorang Mbak marketing kupon diskon amal di mal yang ngotot kepada saya, ketika pada akhirnya saya tolak membeli kuponnya: “Kok enggak mau Bu, ini kan berbuat baik. Nolong orang, lho?”. Saya sedikit terkejut. Kebaikan kok dia yang bikin standar? Kan enggak harus saya bikin list pertolongan saya yang lain, yang dia memang tidak perlu tahu? Tangan kiri aja sebaiknya enggak tau saat memberi, ya kan? Di situlah saya agak menyesal memberikan waktu saya untuk mendengarkan dia.
*) Saat lain lagi, saya pernah bilang “iya”, karena seseorang mengatakan bahwa saya punya potensi (yang cocok dengan ajakannya). Padahal saya ingin potensi itu digunakan di tempat lain, yang lebih cocok buat orang seperti saya. Dan benar, ternyata ketika yang kita katakan berbanding terbalik dengan yang kita inginkan, sungguh tersiksa dan tidak lega.
*) …. dan masih ada deretan cerita lain yang serupa, yang memicu saya belajar membuat batasan, karena saya harus sayang pada diri sendiri dulu.
Jangan takut mengecewakan orang lain, tapi tega mengecewakan diri sendiri. Faktanya, mau iya atau tidak, kalau orang sudah enggak suka sama kita, mereka tetap tidak bisa disenangkan dan tetap tidak suka. Sementara yang memang sudah paham, menghargai pilihan dan percaya, saat kita bilang “tidak” pun akan tetap baik-baik saja, tidak ada yang berubah. Harapan orang lain, kekecewaan orang lain, menurut teori dan buku yang saya baca, sudah jadi urusan orang tersebut. Jadi sekarang, tugas kita tetap berbuat baik sesuai kemampuan dan sesuai kata hati, fokus ke tujuan perjalanan hidup kita sendiri. Jangan sampai jadi orang yang bisa baik banget ke orang lain, tapi mendzolimi diri sendiri.
Seperti cerita bulan November 2022 di awal tulisan ini, saat mau menulis sambil menunggu anak nonton itu, saya membela keinginan diri sendiri. Menentukan prioritas saya.
Hari itu, saya tidak membeli apapun yang memang tidak saya butuhkan.
Saya juga tidak terpaksa mendengarkan, tapi hati bete.
Saya juga tidak perlu jutek saat menolak dan menyatakan keinginan saya untuk tidak diganggu.
Tapi pastinya, hari itu… satu tulisan, berhasil saya bawa pulang, sesuai yang saya targetkan.
Saya lega.
Bilang “tidak” untuk kebaikan diri, sangat tidak apa-apa, daripada “iya” yang membuat kesan baik, tetapi membungkus kekecewaan, gerutu dan ketidakikhlasan dalam diri. Awalnya berat, tetapi ternyata bikin lega.
Never stop learning, because life never stops teaching. Begitu kan?
(Salah satu catatan lama yang tertinggal di sebuah folder di tahun 2022)
Note:
Biasanya perkara membuat batasan/boundaries ini akan tertahan di rasa ragu dalam diri: Ini self-love atau selfish ya? Saya juga masih begitu untuk beberapa hal. Tapi kayaknya asal kita ikhlas dalam membuat keputusan (baik Ya atau Tidak), lalu kita lebih banyak merasa lega dan tidak menyakiti diri sendiri, itu lebih dekat ke self-love. CMIIW… Selebihnya silakan browsing untuk isu boundaries, Self-love VS Selfish ini.
Saya berharga, kamu juga berharga… dan masing-masing kita berhak bahagia. Butterfly hug dulu dong….