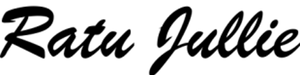Air mata terus menerus mengalir di pipinya. Membayangkan ketika ia melahirkan Rara, Tyo dan Cira. Tiga anak, tiga kelahiran yang membekas.Tiga cerita yang berbeda. Mengingat langkah pertama mereka, celotehan pertama mereka, mengingat kepanikan ketika salah satu dari mereka sedang sakit.
Ia juga rindu pegangan tangan dan pelukan Raka. Kekasihnya, suaminya.
Ini kali pertama isi otaknya dipenuhi pikiran-pikiran yang begitu banyak dan detail. Mengingat masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Hanya satu benang merahnya: semua tentang keluarga. Tidak ada kekhawatiran dan kerinduan Tiara melebihi kekhawatiran dan kerinduannya pada keluarga. Pada mereka yang selalu ada saat susah dan senang, selalu ada pada saat ia membuka mata di pagi hari dan menutup mata di malam hari. Juga pada mereka yang selalu ada dalam hati walau berjauhan. Keluarga kecilnya, ibunya, kakaknya, mertuanya, dan beberapa sahabat terdekatnya.
Saat itu, pertama kalinya Tiara merumuskan kata ‘penting’, ‘utama’ dan ‘cinta’. Mengenali yang tidak penting, bukan utama, hingga kesia-siaan.
***
Detik berhenti di depan sebuah pagar. Di balik pagar itu, terdapat halaman luas, yang jauh lebih indah. Indah sekali. Bunga-bungaan, Sungai yang airnya bening dan sepertinya segar sekali. Kalau memang ini adalah jalan menuju Sang Maha Pencipta, maka di balik pagar itu sepertinya surga. Entahlah. Tiara ragu, dan berhenti. Ia menatap punggung Detik. Lalu, Detik berbalik.
“Nah, kita sudah sampai”
Tiara memandangi pagar yang tidak tinggi. Pagar itu tampak biasa saja. Bahkan tidak berbentuk gerbang-gerbang tinggi dengan benteng kokoh. Tidak. Ini pagar kayu biasa saja. Rendah. Tak lama kemudian, muncul beberapa orang di seberang sana memakai baju putih-putih. Mereka tampak muda dan bahagia.
Betapa terkejutnya ia melihat almarhum ayahnya ada juga disana. Ia tersenyum manis sekali. Wajahnya bersih dan bercahaya. Tiara terharu, betapa selama ini ia menahan rindu, ingin bertemu dengan Ayah. Perempuan itu melambaikan tangannya. Ayah balik melambaikan tangan.
“Mereka menyambutmu, Tiara. Begitu melewati pagar ini, kamu sudah tidak lagi hidup di dunia.”
“Apakah aku bisa memeluk ayahku?”
“Nanti, setelah kamu melewati pagar ini. Pagar pembatas antara hidup dan mati”
Tiara berpikir. Ia tampak ragu. Ia begitu ingin menghambur ke dalam pelukan Ayah, tapi ia masih memikirkan anak-anak, suami dan ibunya.
“Mmm Detik, bolehkah aku berbicara dengan Tuhan?”
“Tuhan itu dekat, Tiara. Aku saja bisa membaca pikiranmu, apalagi Tuhan. Bicaralah dalam hati. Ia Maha Mendengar”
Tiara menundukkan kepalanya, memejamkan matanya.
Tuhan, aku begitu merindukan Ayah. Tetapi aku juga belum siap meninggalkan anak-anakku, sungguh. Aku tahu bertemu dengan-Mu adalah hal indah yang pasti akan terjadi, namun aku ingin bertemu dengan-Mu tidak dalam keadaan menyesal karena lalai menjadi ibu, menjadi anak, menjadi istri.
Tuhanku, apabila ini adalah sebuah pelajaran besar bagiku, aku sepenuhnya mengerti. Aku begitu mengerti maksud-Mu. Izinkan aku untuk kembali kepada keluargaku. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan sekali lagi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Namun, apa pun keputusan-Mu, aku sepenuhnya berserah kepada-Mu.
Tiara menangis, dan mengangkat kepalanya, menoleh kepada Detik. Perempuan itu mengangguk. Ia mencoba untuk ikhlas. Ia siap bila harus melewati pagar, siap bila masih diperbolehkan berkumpul bersama keluarga.
Detik menepuk pundak Tiara.
“Kamu boleh pulang, Tiara. Kepada suamimu, kepada anak-anakmu.”
Senyum Tiara mengembang, sambil menganggukkan kepalanya. Matanya basah, kini karena terharu. Ia menatap ayahnya. Di seberang sana, Ayah mengangguk. Mengerti bahwa waktu anak perempuannya belum tiba. Tiara mengangkat kedua telapak tangan ke dadanya, dan tersenyum.
“Detik, tolong sampaikan pesanku untuk Ayah. Katakan padanya bahwa aku sangat berterima kasih pada Ayah atas semua yang telah dilakukannya untukku. Aku juga meminta maaf karena begitu jarang mengatakan bahwa aku sayang padanya. Padahal, aku teramat sayang dan bangga padanya. Aku akan selalu menyebut Ayah dalam rindu berbalut doa.”
Detik mengangguk pelan. Ia tersenyum.
“Ingatlah momen ini, Tiara. Kematian itu dekat. Sedekat yang kamu rasakan sekarang. Kehidupan dan kematian itu pembatasnya tipis sekali. Aku yakin kamu mengerti kini, tentang yang penting dan yang tidak penting. Kurasa, kamu akan lebih bijak dalam mengisi hidupmu pada kesempatan kedua ini,” katanya, sambil tersenyum.
“Nah, sekarang kembalilah ke keluargamu sampai nanti, bila waktunya benar-benar tiba.”
Tiara menganggukkan kepala pada Detik. Ia tidak hendak dan tidak perlu berkata apa-apa lagi padanya. Bukankah Detik tahu semua tentang dirinya? Pastinya, ia juga tahu bahwa Tiara telah mengerti semuanya, kini.
Tiara melambaikan tangan sekali lagi pada Ayah. Ia berada di antara rasa sedih dan bahagia. Ah, sesungguhnya ia merasa bahagia. Walaupun belum bisa bersama dengan Ayah, setidaknya ia tahu ayahnya juga bahagia, dan tak sakit lagi. Ia lebih bahagia, karena bisa segera kembali ke rumah.
Tiara membalikkan badan dan berlari sekencang-kencangnya menghampiri tittik hitam yang tadi ia lewati. Kali ini, ia tidak takut terantuk, tidak takut terbentur. Ia hanya ingin kembali pada Raka dan anak-anaknya. Secepatnya ia berlari, dan berlari…
Tiba-tiba, ada sesuatu, seperti kilatan cahaya mengenai tubuhnya.
Lalu, gelap. Waktu berhenti.
***
Samar-samar terdengar suara. Masih gelap, ia tidak bisa lihat apa-apa. Pendengarannya ia pertajam. Suara itu, suara kecil itu… Suara yang biasanya membuat Tiara merasakan segala rasa. Rasa terganggu, rasa rindu, rasa geli, rasa yang terkadang mengundang amarah, sekaligus menggugah rasa keibuannya. Kali ini, ada rasa rindu yang tak tertahankan. Sayang, matanya terasa berat untuk dibuka.
“Mama, Mama… bangun!” Suara itu memaksanya untuk membuka mata, namun susah rasanya. Kepalanya terasa sakit.
“Mama, maafkan Tyo…” suara anak lelakinya juga terdengar. Tentu saja, Tiara memaafkan anak lelakinya itu. Tanpa peristiwa ini, ia mungkin akan selamanya lalai. Nanti, bila ia sudah sanggup berkata-kata, sepertinya ia yang harus meminta maaf pada anak-anaknya.
Tiara mendengar isakan anak sulungnya. Rara, tidak berkata-kata. Tapi tangisnya terdengar di telinganya, di sela suara-suara lainnya. Tiara tersadar betapa anak-anak mencintainya, dan menginginkan kehadirannya. Justru dirinyalah yang sering lalai dalam caranya mencintai mereka.
“Bu, tenang ya, Bu! Tarik napas, buka matanya pelan-pelan saja” kali ini, suara yang terdengar asing baginya.
“Tiara, tenang, Sayang… kami semua ada di sini” terdengar suara lelaki yang membuat jantungnya selalu berdebar. Suara lelaki yang melamarnya, yang memeluknya setiap malam, yang dengan sabar mendengar setiap ceritanya, lelaki yang menjadi bapak dari anak-anaknya.
Samar-samar, bayangan mereka mulai terlihat. Sosok-sosok yang ia kenal. Sepertinya, ia sedang di rumah sakit, karena selain mereka, ada beberapa sosok berpakaian putih-putih berlalu-lalang. Perlahan, ia mencoba menggerakkan tangannya, kakinya. Bisa, meskipun semua terasa berat.
Aku masih hidup! Tiara terharu. Ia menjadi lebih tenang. Ia masih bisa menunggu seluruh matanya terbuka, seluruh badannya bergerak. Ia akan sabar menunggu untuk bisa memeluk kecintaannya. Mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka, memerhatikan satu persatu. Mencintai, dalam bentuk dan dengan cara yang kini sepenuhnya ia mengerti.
Mengingat Sang Detik, ia lebih mensyukuri dan menghargai momen dengan mereka yang dicintai dan mencintainya. Tidak ingin lagi ia melakukan kesia-siaan. Tidak ingin merugi.
Mensyukuri kesempatan hidupnya yang kedua.
Detik, demi detik.
Demi masa yang tersedia.
(2014)
Pertama kali dipublikasikan di platform Storial.co, September 2018