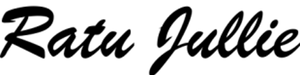Lorong itu gelap dan dingin. Di ujung sana, ada setitik cahaya. Tetapi sepertinya itu jauh sekali. Perempuan itu kebingungan. Ia berjalan perlahan, takut menabrak sesuatu. Takut juga tangannya menyentuh wujud yang tidak diharapkannya. Kegelapan yang sangat pekat di sekelilingnya itu, tidak dapat dilihat batasnya.
Aku ada di mana? Ia bertanya dalam hati.
Ia mencoba menangkap suara, namun percuma. Senyap. Hanya satu hal yang terdengar: setiap helaan napasnya sendiri. Ia bisa mendengar dirinya menarik napas dan mengeluarkannya terburu-buru.
Ia mencoba menyesuaikan penglihatannya di dalam gelap. Memicingkan, membuka, mengerjapkan mata, percuma saja. Gelap. Hanya satu yang bisa dilihatnya: sinar di ujung sana. Sepertinya itu jalan keluar.
Seingatnya, ia fobia gelap. Setiap mati lampu di malam hari atau berada di ruang tertutup yang gelap, dirinya selalu panik. Mengingat itu, kini ia jadi panik betulan. Napasnya menjadi terburu-buru, karena ia sangat ingin mencapai sinar itu. Apa daya, ia berjalan dalam kegelapan.
Ia berjalan, tapi tak sampai- sampai. Dalam kepanikan, satu-satunya yang lambat adalah jalannya. Bagian tubuhnya yang lain bergerak tak tentu arah. Ia takut badannya, kepalanya terbentur sesuatu. Ia sedikit membungkuk. Takut-takut, ia julurkan tangannya ke depan, berusaha menggapai. Saat ini, pikirannya sangat kacau.
Apa yang sedang terjadi? Di manakah ini? Apakah ini mimpi? apa aku sedang melakukan perjalanan astral? Ia berpikir tentang saat ini, lalu berpikir juga ke belakang. Apa yang sebelumnya terjadi? Sedang apa aku sebelum berada di sini?
Lalu, teringat sesuatu. Ia menghentikan langkahnya. Menarik napas pelan-pelan sekali. Telapak tangannya, ia simpan di dadanya. Merasakan detak jantungnya sendiri. Debar jantungnya yang tadi berdetak begitu kencangnya, perlahan mulai teratur. Ia bisa mendengar napasnya tak lagi memburu. Tidak lagi merasa panik. Ia merasa beruntung sekali masih sanggup mengingat teknik pernapasan untuk relaksasi.
Ia mulai mengontrol dirinya, dengan mengingat kembali siapa dirinya.
Namaku, Tiara. Aku… Aku… Aku… Aku menikah dengan Raka. Sudah, sudah lama. Aku sudah punya anak. Tiga orang anak. Rara, anak pertamaku, perempuan, sudah berusia 10 tahun. Tyo, anak lelakiku, umurnya 7 tahun dan si kecil Cira, baru dua hari lalu berulang tahun yang ke-4.
Hatinya bersorak, karena mampu mengingat hal-hal penting. Ia mengingat dirinya!
Tiara mengunjungi ingatannya yang lebih jauh lagi dari itu. Sesaat ia mengingat ibunya, kakaknya dan almarhum Ayah. Ia sempat mengunjungi masa kecilnya sebentar saja. Hanya untuk mengonfirmasikan siapa dirinya.
Meskipun masih sangat bingung tentang saat ini, tentang kegelapan ini, tentang sinar kecil di ujung sana, yang entah kapan bisa ia capai, setidaknya ia sudah mulai merasa tenang. Ia mulai berjalan lagi perlahan-lahan.
Tiara hanya fokus pada napasnya, juga fokus pada sinar kecil di ujung sana. Kali ini, ia tidak lupa berdoa agar dapat berjalan dalam gelap menghampiri sinar itu.
Pelan-pelan, sinar terang itu membesar. Semakin besar, sebesar dirinya. Ia sudah sampai. Ia menyipitkan matanya, menahan silau. Ia berusaha menyesuaikan matanya yang dari tadi hanya mengenal sepenuhnya gelap dan setitik cahaya.
Belum lagi matanya terbiasa dalam terang yang menyilaukan, tangan seseorang menepuk bahu kanannya. Ia menoleh, namun belum bisa melihat dengan jelas orang yang menepuk bahunya tadi. Samar-samar yang terlihat hanyalah bayangan. Sepertinya seorang lelaki. Lebih tinggi darinya.
“Kamu, kamu siapa? Aku di mana?”
“Tiara, tenang dulu. Kamu sedang dalam perjalanan yang membahagiakan, bersiaplah”
“Kamu tahu namaku? Perjalanan apa? Membahagiakan? Aku… aku tidak mengerti”
“Ya, tentu saja aku tahu namamu, segala tentangmu. Aku akan menemanimu pulang”
“Pulang? Pulang ke mana?”
“Penciptamu, Tiara. Ini waktumu. Ini saatmu”
“Maksudmu?”
“Waktumu di dunia sudah selesai, Tiara…”
Tiara terenyak mendengar itu semua. Ia menggelengkan kepala. Ia belum siap meninggalkan dunia, meninggalkan anak-anak.
“Tidak! Tidak! Kamu pikir kamu siapa? Malaikat?”
Ia hanya tersenyum. Tidak mengangguk, tidak menggelengkan kepala.
“Panggil aku: Detik”
Tiara mengernyitkan alis dan dahinya. Dalam semua keterasingan yang serba mendadak ini, ia masih harus merasakan sesuatu yang janggal. Seorang lelaki di depannya bernama Detik. Biarpun itu adalah kata yang familiar, tapi terlalu lucu untuk sebuah nama, apalagi nama lelaki. Ini sungguh sebuah komedi.
Terbesit dalam pikirannya bahwa ini adalah sebuah jebakan reality show atau semacamnya. Ia sempat berharap dalam beberapa menit ke depan akan muncul orang-orang yang dikenalnya. Mengejutkannya dengan berteriak : Surpriseee!
Sempat Tiara menebak-nebak orang iseng di belakang peristiwa ini. Namun, ia juga sadar bahwa ada momen di mana ia tiba-tiba berada disini. Apakah ia terbius? Reality show macam apa yang skenarionya memakai obat-obatan kimia macam itu?
Detik memandanginya. Ia membiarkan pikiran Tiara menari-nari kesana kemari. Sampai ada jeda. Buntu.
“Bukan, Tiara, ini bukan reality show”
Apa pula ini? Pikir Tiara.
“Kamu bisa membaca pikiranku juga, Detik?”
Detik mengangkat alisnya sambil tersenyum. Mengonfirmasikan bahwa ia memang bisa membaca pikiran perempuan itu.
“Ini memang realita, sebuah kenyataan. Kamu dipanggil untuk pulang.” Lalu, Detik mengulurkan tangannya.”Ayo, kita pulang!”
Spontan, Tiara menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya. Persis seperti anak kecil. Persis seperti kelakuan si bungsu, Cira. Kalau diajak pulang ke rumah dari taman bermain, Cira akan menyembunyikan tangannya, lalu berlari menghindar.
Kalimat ‘Kamu dipanggil untuk pulang’, sesungguhnya adalah kalimat biasa saja, yang sering terdengar selama hidupnya. Kali ini, kalimat itu membuat jantungnya berdetak kencang, lalu tiba-tiba berhenti. Ia juga ingin bisa berlari seperti Cira. Tapi kemana? Ia bahkan tidak tahu mereka berada di mana, ia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa ada di sana.
“Aku, belum siap. Aku belum mau mati. Belum mau!” Tiara berteriak, lalu menangis.
“Hei, hei… Tiara. Bukankah kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memilih waktu kematiannya sendiri?”
Perempuan itu mengangguk pelan. Ia tahu, tapi…
“Tapi apa, Tiara? Kamu tidak menyangka secepat ini?”
Perempuan itu kembali mengangguk. Mulutnya bergetar.
Detik membimbingnya duduk. Akhirnya Tiara bisa melihat apa yang dari tadi dipijaknya, sejak berhasil mencapai cahaya. Mereka berdua duduk di hamparan rumput yang luas, seakan tak berujung. Tidak ada apa-apa selain rumput hijau sekeliling mata memandang.
“Aku…aku masih ingin bersama anak-anakku. Aku…aku masih ingin bersama-sama dengan Raka hingga tua. Berdua dengan Raka melihat anak-anak kami kuliah, menghadiri wisuda mereka, melihat mereka menikah dan menimang cucu-cucu kami”
Tiara kembali menangis. Detik memandanginya. Menunggunya. Masih ada yang ingin perempuan itu katakan.
“Ini tidak adil, Detik! Aku masih muda, cara hidupku sehat, tidak pernah macam-macam. Tidak pernah aku berniat untuk memperpendek umurku”
“Iya, tapi Yang Maha Kuasa sudah menentukan jatah waktumu. Ini saatnya”
“Kapan aku mati? Maksudku, bagaimana aku bisa mati? Aku tidak ingat sama sekali”
“Kamu, telepon genggam, rengekan Cira dan tangga. Kamu ingat?” Detik menyebutkan kata-kata, yang sepertinya adalah kata-kata kunci yang harus ia rangkai untuk mengingat peristiwa sebelum ia berada di sini.