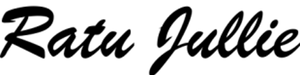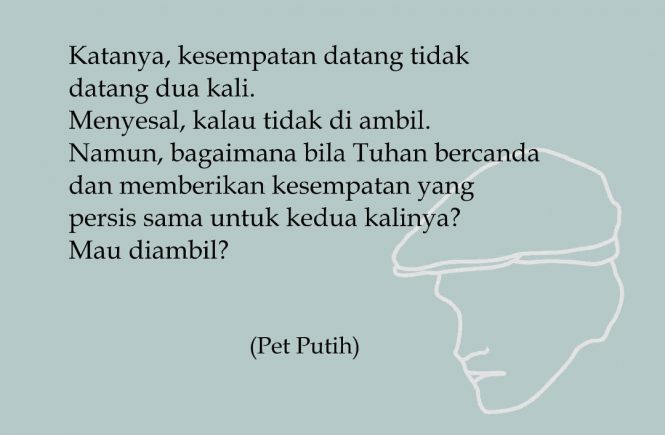I’m 33 for a moment
Still the man, but you see I’m a ‘they’
A kid on the way, babe
A family on my mind
…
(100 years, Five for fighting)
Kamu mati, kataku datar menyimpulkan. Sebelumnya aku berusaha mencari padanan kata lain, menyibukkan dan menghibur diri. Meninggal (karena kamu manusia). Wafat (karena kamu dekat), Mangkat (karena bagiku, kamu terhormat). Pilihan apa pun, sesungguhnya sama saja, bukan? Kamu pergi dan tidak akan pernah kembali. Biarpun aku bilang kamu mangkat, tidak akan mengurangi takaran sedih ini, sedikitpun.
Rohmu meninggalkan jasadmu? Baiklah, kami semua mengubur jasadmu. Jasadmu ada dalam kubur. Lalu aku – karena kita begitu dekatnya – mulai bertanya : rohmu ada di mana? Aku, menggila mencari jawabannya.
Banda Aceh-Bandung itu jauh, Sayang… maka tidak salah rasanya saat aku mendapat telepon dari Ibu di Bandung, penyakitku kambuh. Lalu, keluarlah asam dari lambung yang berbentuk busa itu. Stress. Psikosomatis. Aku ini di Banda Aceh. Sesungguhnya, berita pastinya tidak terlalu jelas karena isakan bernada panik lebih terdengar keluar dari mulut wanita yang kita sebut Ibu itu. Aku tahu arahnya, aku tahu gawatnya. Akhirnya kamu mau dibawa ke rumah sakit. Napasmu pendek-pendek. Sesak.
Tahukah kamu? Mulai detik itu, aku mengepak pakaian sambil mual-mual. Kalau tidak ada kakak iparmu, maka aku akan menjadi manusia paling bego. Berharap menjadi Doraemon yang punya ‘pintu kemana saja’, atau setidaknya punya ‘baling-baling bambu’ yang bisa membawaku terbang ke Bandung saat itu juga. Aku mengepak barang dengan pesimis. Pesawat terakhir dari Banda Aceh ke Jakarta tinggal beberapa jam saja, kami tanpa tiket, waktu itu Hari Minggu, dan dari Jakarta masih ada beberapa jam lagi harus kami tempuh menuju Bandung. Aku pesimis. Pikirku, biarpun akhirnya kami bisa terbang ke sana, betapa Banda Aceh-Bandung itu sungguh jauh…
Sungguh perjalanan panjang yang paling menyiksa, yang pernah kuingat, dengan perasaan yang bercampur aduk seperti itu.
Hari Ketiga
Aku mendatangi kuburmu. Masih ada bunga-bunga yang dua hari lalu ditaburkan di atasnya. Hanya saja, semuanya mulai layu kecokelatan. Bagiku, ditinggal mati keluarga dekat nyatanya adalah saat yang tepat untuk menyambut pikiran-pikiran tidak logis dengan tangan terbuka. Aku begitu permisif terhadap versi apa pun tentang roh, tentang hal-hal gaib. Asalkan itu menenangkan aku, memuaskanku. Di depan kuburmu aku bertanya pada anakku, keponakanmu yang berumur dua tahun itu. Dimanakah pamanmu? Terlihatkah olehmu?. Segera saja aku tersenyum puas saat ia mengatakan ini itu, konsisten atau tidak, masuk akal atau tidak. Aku menyambut apa pun ‘gosip’ tentangmu, tentang rohmu.
Cengkareng-Bandung
Rasanya mobil sewaan yang kami tumpangi dari Cengkareng ke Bandung berjalan seperti siput. Yang pada akhirnya bisa membuatnya seperti berlari adalah berita dari telepon genggamku. Lagi. “Sudah sampai mana? Jangan pulang ke rumah dulu. Langsung saja ke rumah sakit. Dia kritis”. Degup jantungku, berlomba cepat dengan jalannya mobil yang seperti kuda terpecut itu. Ironisnya, pikiranku melambat. Ia mulai melakukan monolog yang kalau terdengar orang, pasti aku akan dimaki. Aku mulai berbicara dengan Tuhan, bahkan denganmu.
Tuhan… apakah Engkau betul-betul akan mengambilnya?
Tuhan tidak menjawab, tetapi aku seperti tahu jawabnya.
Lalu, aku berusaha mencapai hatimu. Aku rasa, kamu bisa mendengar.
Hai, Adikku… akankah kamu meninggalkanku hari ini? Baiklah, hari ini sama dengan peristiwa Supersemar. Mudah diingat. Atau kamu memilih lusa? Bukankah 13 adalah angka kebanggaanmu? Angka kelahiranmu?.
Aku melawan kegilaan ini. Setelah meminta ampun pada Tuhan atas monolog tak karuan tadi, akhirnya hatiku membisikkan lagi kata-kata pada hatimu. Kali ini, hatiku sedikit lunak dan lembut.
Dik… tunggulah aku. Sebentar lagi aku sampai….
Pundakku diusap lengan lelakiku. Mataku memanas.
Hari kelima
Aku berharap semua ini mimpi. Aneh, bukan? Rumah ini sudah menyaksikan tiga kematian. Tetapi aku tak kunjung terlatih. Pengetahuan bahwa kematian adalah suratan, juga tak mempan. Ternyata ini memang bukan tentang kematian, tetapi tentang kehilangan. Tentang rindu. Lima hari, dan aku semakin ingin bertemu.
Doa dan Shalat terus dilakukan, tetapi aku masih tetap bertanya dan tetap menebak-menebak keberadaanmu. Keberadaan rohmu. Aku seperti melakukan dua hal yang berbeda. Mencoba untuk tetap dalam keimanan dan keikhlasan, tetapi mengorek-ngorek berbagai macam cara untuk bertemu denganmu. Datanglah dalam mimpi, sayang… pasti kamu tahu caranya.
Rumah Sakit, Bandung
Mereka semua berdiri ketika kami datang. Mata mereka sembap. Napasku mulai memburu. Bergegas aku melewati lorong dingin, mendekatimu. Nama Tuhan aku sebut demi melihat napasmu yang juga memburu, ditolong alat bantu. Kalau hati bisa bernapas, maka ia tengah sesak. Pedih. Perih. Saat ini yang disebut simalakama adalah doa. Harus berdoa apa aku?
Betul, aku memang pernah diberi tahu tentang cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya, adalah sanggup melepaskan. Tetapi itu artinya aku harus kehilanganmu. Perjalanan adik-kakak kita akan terhenti di sini. Aku melihat suamiku dan anakku. Kakak ipar dan keponakanmu itu memang ada. Tetapi aku juga ingin kamu tetap ada sampai kita tua. Menanti kelahiran anakmu yang keponakanku, menghadiri pernikahan anak-anak kita. Melihat rambut kita memutih, kulit kita kisut mengeriput.
Membahas gigi palsu yang terlihat saat kita terkekeh-kekeh mengingat masa kanak-kanak kita. Itu, itu…adalah masa depan yang kita bayangkan, bukan?
Harus berdoa apa, aku? Aku menengadah. Begitu besarnya yang memilikimu. Aku ini hanya debu, dan tiada hak atas dirimu. Akhirnya, teringat bahwa Ia ada, dan Ia sutradara terbaik. Akhirnya, Dik, aku serahkan kamu pada-Nya, dan setelah menciummu aku berlalu, karena malam telah larut. Dalam gendongan, keponakanmu bergelayut. Mata ibunya telah basah.
Pagi datang hanya dalam dua jam. Sebuah kabar lewat telepon datang lagi. Kamu pergi selamanya. Aku berteriak kencang, lalu ternganga. Aku mengedip-ngedipkan mata, tetapi air mata kalah oleh suara. Hanya ada isak. Mereka bilang, itu artinya aku teramat sedih hingga air mata tertahan duka dalam, tak bisa keluar. Hati ini seperti luka menganga, yang disiram alkohol. Perih. Sejak itulah aku mencarimu.
Bagaimana caraku untuk berbicara padamu? Biasanya aku bisa bicara denganmu kapan aku mau. Langsung berhadapan atau lewat telepon. Aku akan kehilangan cerita darimu, tentangmu. Kamu tahu bukan, bahwa kamu adalah salah satu pemilik cerita kanak-kanakku?. Aku ada, kamu ada. Aku mewariskan rahim ibu kepadamu. Lalu, apakah aku harus merelakanmu begitu saja?Oh, Tuhan….
Hari ketujuh
Aku masih berjibaku mencarimu. Shalat dan doaku, diselingi dengan membaca petunjuk ini itu tentang cara bertemu dengan orang-orang yang sudah mati. Diselingi dengan tanya sana sini tentang kemungkinan keberadaan rohmu di rumah. Bahkan terkadang isi doaku adalah hal yang mungkin tak ingin didengar Tuhan.
Aku ingin kamu kembali dan bercerita tentang sakratulmaut, tentang rasanya dicabut nyawa, tentang cara menghubungimu ketika aku rindu. Aku berdoa agar kamu setidaknya bisa memberitahuku bahwa kamu juga rindu padaku, sayang padaku. Setidaknya kamu bilang padaku bahwa kamu baik-baik saja. Bukankah itu semua sering kita lakukan sebelumnya?
Aku dan kamu bersama selama puluhan tahun. Aku tahu bagaimana menghubungimu dan kamu selalu tahu aku berada dimana. Jarak kita hanya sejauh ibu jari yang tertempel pada telepon genggam, jarak kita hanya hitungan detik di dunia maya. Jarak terjauh dan terlama fisik kita hanya antara satu waktu cuti, ke waktu cuti yang lain. Tidak sanggup rasanya terpisah denganmu lebih lama dari itu.
Aku seperti musuh dalam selimut bagi Tuhan. Tetap melakukan shalatku, mengirim doaku, tetapi tetap mencari cara bertemu denganmu. Meminjam rasa tenang dari ibadahku, tetapi memperbolehkan dosa demi satu kali saja pertemuan denganmu. Kalau bisa, berkali-kali, sampai aku mati juga.
Pemakaman
Kamu terbujur kaku. Kamu mati, kamu meninggal, kamu wafat, kamu mangkat. Apa pun yang mereka sebut. Apa pun yang pantas diucapkan dari kakak kepada adiknya. Kamu tidak ada lagi. Titik.
Perasaanku yang sedih perih pilu itu harus aku bagi dengan bercerita berulang-ulang tentang kematianmu, pada setiap tamu yang datang. Seperti menanamkan sebuah chip, berisi konsep tentang luka. Cerita yang bahkan masih tidak aku percaya, harus aku ulang terus dan terus sepanjang hari. Hanya satu kali aku berhasil menamatkan doaku di samping jenazahmu. Itu pun diselingi rengekan keponakanmu. Di mana aku harus menempatkan sedih terdalam ini? Doa yang terpotong cerita proses kematian, ciuman yang tak terabadikan, isak yang dijeda oleh senyuman, lalu sudah. Kamu harus dimakamkan.
Apa? Ini saatnya? Sudah berpisah dengan rohmu, lalu harus berpisah lagi dengan jasadmu? Tidakkah salah satu darimu bisa aku simpan? Bukan barang-barangmu. Aku ingin kamu.
Akhirnya, aku melangkah juga ke tanah mungil milikmu itu. Aku, kakakmu. Kamu, adikku. Kita berbagi cerita dan berbagi hidup bersama. Sulit diterima bila selanjutnya, di dunia ini, aku hanya bisa bertemu dengan namamu yang tertulis di atas nisan. Bagaimana dengan kenyataan bahwa tidak akan ada lagi kamu dalam foto keluarga kita?
Hati yang tengah menjerit ini, dijeda oleh rasa takjub, melihat pemakamanmu. Melihat teman-temanmu. Tangis dan genggaman tangan mereka seperti membuatku jatuh di atas rerumputan. Ia tetap dinamakan jatuh, tetapi tidak terlalu menyakitkan. Aku tidak sendirian, aku bertahan. Aku harus kuat.
Empat puluh hari.
Aku melihat diriku berbalut mukena. Mukaku merah padam, malu pada Tuhan. Aku menunduk. Sajadah terbentang, menyalak menantang. Aku mulai takut. Akhirnya aku jatuh terduduk ketika nama Tuhan mengalun keluar dari bibirku.
Aku melihat diriku di dalam cermin. Mataku sembap, hidungku merah. Aku menyisir rambutku sambil berpikir. Tiga puluh tiga tahun sejak kamu lahir, rupanya cukup menurut Tuhan. Aku bangga kita ini dekat. Kita memang tidak pernah membangun tembok diri yang membuat hati kita berjarak. Iya, aku berduka dan terluka. Tetapi aku tidak harus terlihat lusuh dan kusut bukan?
Sambil menyisir, aku tersenyum. Teringat kamu, rambutmu dan sisir. Tiga hal yang selalu berkolaborasi dengan solidnya, mencapai kata ’sempurna’. Rambutmu yang super pendek itu biasanya kamu sisir jauh lebih lama daripada waktu menyisir seorang wanita berambut panjang. Sambil menyisir, aku tergelak. Kamu pasti senang melihat sisir ada ditanganku. Kamu pasti puas, karena kerap menyindir tentang rambut ikalku yang disisir tak lebih dari tiga kali sehari, dan sesering apapun – selorohmu – tetap terlihat seperti belum disisir. Aku mulai bisa tersenyum lagi.
Sedihku belum habis-habis. Rinduku apalagi. Aku ingin ziarah lagi. Di mobil, aku menyetel radio. Lagu 100 years dari Five for Fighting, kesukaan kita itu terdengar. Kebetulankah? Atau kamu memang tengah bersamaku?
…
Fifteen there’s still time for you
Twenty two, I feel her too
Thirty three, you’re on your way
Every day’s a new day
…
Tiba-tiba aku tersadar.
Hei, Kamu ada sekarang! Saat ini! Bahkan, setiap saat.
Saat aku tengah menyisir rambut, saat lagu kesukaan kita terdengar, saat aku bersama ibunda dan adik kita, saat aku mencandai keponakanmu…
dan aku yakin, kamu akan tetap ada dalam hatiku, di setiap langkahku, sampai kita bersama lagi dalam satu dimensi, nanti…
Terima kasih,
untuk tiga puluh tiga tahun yang telah kamu goreskan dalam kehidupanku,
untuk membuatku tetap tersenyum, bahkan tertawa, saat mengingatmu,
walau kamu telah pergi.
Adik, aku…mencintaimu.
(2012)
di publikasikan pertama kali di platform wattpad tanggal 16 Agustus 2018