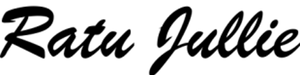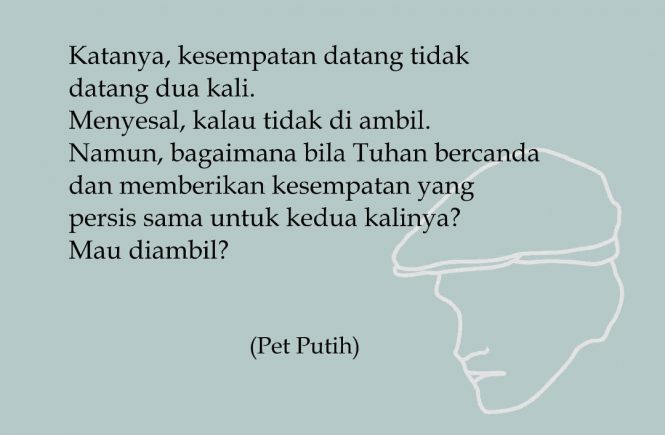Cerita Pendek (Fiksi)
Saya berlari memasuki gerbong kereta api yang siap-siap berangkat.
Pas-pasan! kata saya setengah lega, setengah mengutuk. Saya tidak suka nyaris terlambat, apalagi betul-betul terlambat. Saya lebih suka menunggu, daripada ditunggu. Dalam menunggu saya bisa mendapatkan pemandangan, ilmu dan cerita baru. Sementara dalam ditunggu, biasanya yang saya dapat adalah tegang dan letih. Seperti sekarang ini.
Saya masih berdiri di ujung lorong gerbong. Menenangkan diri, mengatur napas, lalu saya berjalan mencari nomor bangku. Beberapa bangku terlihat kosong. Sudah saya perkirakan, karena ini kereta pagi dan bukan akhir minggu atau awal minggu. Saya berharap menjadi salah satu penumpang yang beruntung tidak mendapatkan teman sebangku hari ini.
Dari beberapa bangku bagian belakang, saya bisa melihat bangku saya kosong. Artinya mungkin saya bisa selonjoran dan membaca buku dengan tenang karena tidak perlu berbagi kursi dengan penumpang lain. Tidak perlu berbasa-basi menawarkan makanan ketika mau makan. Tidak perlu tersiksa bila mendapatkan teman seperjalanan yang cerewet dan kurang asyik.
Mudah-mudahan memang betul-betul kosong, hati berharap, walaupun sesungguhnya saya juga menyukai rasa penasaran dan tebak-tebakan tentang siapa calon teman seperjalanan. Kalau ia menyenangkan, berarti saya dapat ilmu dan kawan baru, kalau menyebalkan, saya bisa menertawakan diri atas kesialan saya hari itu. Satu hal yang pasti, seperti apapun teman seperjalanan, saya pasti akan mendapatkan cerita. Tetapi sejujurnya, hari ini saya sedang malas berbasa-basi.
Traveling bag kecil yang tadinya saya gantung di pundak, saya simpan di bawah, dekat kaki. Tidak makan tempat, jadi duduk lebih nyaman. Saat saya meraba-raba tas tangan untuk mencari buku yang akan saya baca, kereta mulai berjalan pelan-pelan sebelum kemudian berlari. Yes! Bangku sebelah memang kosong!
Saya mencari posisi ternyaman di tempat duduk yang seharusnya untuk dua orang itu. Sebelum mulai membaca, saya melihat pemandangan di luar jendela. Ini masih dalam kota Bandung. Melewati pintu lintasan kereta api, rasanya seperti peserta pawai artis. Seakan-akan para pengendara motor, mobil dan becak itu menanti saya lewat. Kadang-kadang saya suka tergoda untuk melambaikan tangan ala Miss Universe pada mereka yang tertahan palang pintu kereta api. Tapi tentu saja umur dan rasa malu selalu menegur saya untuk mengurungkan niat itu.
Saya menarik napas. Sungguh, tidak pernah bisa disangkal bahwa suasana pagi yang ramai dan cuaca pagi yang segar benar-benar menyenangkan. Saya bisa menghirup aroma dan denyut kehidupan yang sebenarnya. Orang-orang itu punya tujuan, dan mereka terlihat bergegas mencapainya.
Setelah puas melihat hiruk pikuk di balik jendela, barulah pandangan saya tebarkan ke bangku seberang yang sejajar. Bangku 12A. Deg! Jantung saya berdebar. Saya membuang muka dengan putaran leher yang pelan, pura-pura tenang. Sementara, hati setengah mati menahan rasa terkejut. Laki-laki itu, sungguhkah dirinya?
Sekitar lima belas menit selanjutnya, saya sibuk meneliti, melirik, mencuri pandang. Di saat seperti ini, keyakinan saya diuji. Hanya satu hal yang membuat saya hampir pasti. Topi pet putih itu. Keyakinan saya lainnya diuji oleh kenyataan bahwa ia naik kereta api sendiri. Sama seperti saya. Mungkin akan lebih mudah bagi saya untuk yakin bila ia bersama tokoh masyarakat lain. Keyakinan saya juga digoyahkan rasa tak percaya bahwa saya mengalami peristiwa yang persis sama dengan dua tahun yang lalu.
Dua tahun yang lalu, di kereta api menuju Jakarta, di suasana pagi yang hampir sama, saya tanpa teman sebangku, Lelaki yang menggunakan topi pet putih juga tanpa teman sebangku. Lebih lucunya lagi, saya saat itu juga dengan ketidakyakinan yang sama. Rasa grogi yang sama.
Kalau saja saya seperti Arin, teman saya yang berani menegur seorang tokoh masyarakat yang ia temui, saya pasti sudah menegurnya. Meminta tanda tangan dan berfoto dengannya. Bagaimana tidak? Keadaan mendukung. Ia dan saya tanpa teman seperjalanan, sementara tiga jam harus kami tempuh, dan suasana pagi begitu segarnya untuk dilewatkan hanya dengan tidur . Sayangnya saya tidak berani. Ia orang besar dan saya bukan Arin.
Maka, dua tahun lalu itu, saya menenggelamkan diri dalam sebuah buku yang pengarangnya tidak terkenal. Sebuah novel berbahasa Inggris, dan itulah satu-satunya alasan saya membacanya. Saya sedang rajin-rajinnya membaca novel apapun yang berbahasa Inggris. Hari itu, saya menenggelamkan diri dalam buku itu, tetapi tidak kepada ceritanya.
Pikiran mengambang. Benarkah itu dirinya? Bagaimana reaksinya kalau ia saya sapa? Mengganggukah bila saya mengobrol, minta tanda tangan dan berfoto dengannya? Apakah saya akan menyesal kalau momen ini berlalu begitu saja? Nyatanya begitu. Saya melewatinya. Tidak menyesal, saya hanya penasaran.
***
Kini, dua tahun kemudian itu, Tuhan seakan tengah bercanda. Keinginan-Nya telah membuat saya dan lelaki itu bertemu kembali. Di situasi yang hampir sama. Yang berbeda, mungkin pakaian kami dan judul novel yang saya baca. Ini tak masuk akal! Maksud-Mu mempertemukan saya dengannya lagi, dengan situasi yang persis sama itu, apa Tuhan? Apa saya harus menyapanya, agar mendapatkan sesuatu dari percakapan itu? Keberanian, misalnya? Atau, terbuka peluang untuk menjadi muridnya? Apa, Tuhan? Atau, Kau memang sedang ingin bercanda saja dengan saya?
Apa pun itu, menit demi menit berlalu tanpa ada jawaban dari Tuhan. Saya gelisah. Tidak tahu harus bagaimana. Saya takut, saya malu dan sedikit gengsi. Setelah menyapanya lalu apa? Saya berpikir keras. Apakah saya harus mulai dari membahas novelnya? Atau tentang manuskrip-manuskrip saya? Atau tentang pet putihnya? Atau bercerita padanya bahwa saya punya mimpi menjadi orang yang banyak karya, seperti dirinya? Bercerita bahwa saya begitu suka menulis?
Yang pasti saya takut, setelah “Hai!” lalu titik. Bingung. Antiklimaks.
Saya membuka halaman baru novel di tangan saya, sambil mencuri pandang. Sepertinya itu memang dirinya. Sesungguhnya hati kecil saya mengenali rasa ini. Rasa takut ditolak, takut kecewa. Bagaimana bila orang yang saya kagumi nyatanya menolak berbicara dengan saya? Saya takut itu. Lebih baik tetap mengagumi sosoknya dari jauh. Lewat layar kaca, lewat media cetak. Sehingga dunia berjalan dengan semestinya: saya orang biasa, ia orang besar. Tidak ada risiko merasa kecewa.
Halaman novel berikutnya baru dibuka seperempat jam kemudian. Bukan novel yang berat untuk dicerna. Pikiran tentang penumpang di bangku seberang itulah yang mengganggu kekhusyukan saya yang biasanya melahap lembar demi lembar dengan cepat. Sejujurnya, saya tidak betul-betul membaca.
Tujuan saya pergi ke Jakarta pun sejenak diendapkan di dasar otak. Padahal, semalaman saya tegang memikirkan wawancara kerja di Jakarta Pusat. Dari ujung mata, saya sempat melihatnya mengambil secarik kertas dan sebuah pena dari saku kemejanya. Ia menulis sesuatu. Menulis!
Sepertinya, itu memang dirinya. Tapi… itu pun tetap tidak merubah apa-apa. Menit sudah berganti menjadi jam, dan saya masih bergulat dengan bisikan tentang kesempatan langka, tentang keberanian. Keduanya mendapatkan perlawanan dari gema yang mengerikan tentang rasa malu, tentang ‘siapalah saya ini’ dan ancaman antiklimaks.
Bangunan serba hijau itu sudah berkelebat. Gambir ! teriak hati saya panik. Bukan kepanikan tentang wawancara itu, Tapi tentang rentang waktu yang sempit untuk membuat keputusan penting: menyapanya atau sekali lagi membiarkannya berlalu. Dan, Oh Tuhan, teganya diri-Mu tak memberikan sinyal-sinyal tentang apa yang seharusnya saya lakukan.
Kaki saya sudah lemas. Menjelang kereta berhenti saya malah grogi. Kemungkinan membiarkannya pergi lebih pasti. Saya masih berpikir: apakah saya akan menyesal atau tidak? (sempat berharap akan ada kesempatan ketiga dari-Nya). Grogi saya semakin menjadi. Berharap lorong tengah gerbong itu cukup luas untuk tidak bertabrakan dengannya saat keluar nanti. Saya memilih untuk cepat keluar, bahkan dengan novel masih di tangan.
Ah! lorong itu memang sempit ! Saya, dirinya, penumpang lain dan para porter Gambir berharap bisa bergerak di saat dan tempat yang sama. Tangan saya tersenggol koper seorang ibu.
Bruk!!! Novel yang saya pegang jatuh.
Laki-laki itu menjulurkan tangannya ke bawah.
“Ini bukunya” katanya tersenyum, mengulurkan buku – yang sungguh beruntung – itu, membalikkan badannya dan berlalu. Dengan mulut ternganga, saya bahkan tak sanggup berterima kasih. Ia idola saya, dan saya penggemar terbodoh di dunia.
Tuhan, pertemukan saya dengannya lagi…saya memelas, menyesal dan gemas.
Tuhan mungkin tengah gemas juga dan berkata “Ah, sudahlah…”
(2012)
Pertama kali diunggah di platform Storial.co bulan September 2018