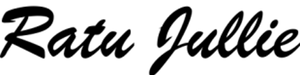Badan Untung letih. Ia rebahan, sambil menahan kantuk. Menunggui Ajeng keluar dari kamar mandi, sambil berpikir apakah ia perlu mandi juga. Namun sepertinya, gerah kalah oleh lelah. Setelah ditunggu, akhirnya keluarlah perempuan yang belum sampai sepuluh jam menjadi istrinya. Untung tersenyum, Ajeng juga. Jelas, mereka bahagia. Mereka sudah lama menantikan saat ini.
Mereka berdua merebahkan badannya di tempat tidur. Untung mengusap kepala Ajeng.
“Kamu happy, Jeng?”
“Iyalah… bersyukur semua berjalan dengan baik”
“Bagian mana yang paling kamu syukuri?”
“Ijab kabul. Momen ketika kamu berjanji pada Tuhan. Itu romantis banget. Kalau kamu? Bagian mana yang berkesan?”
“Sama. Berjanji pada Tuhan untuk bertanggung jawab atas kamu. Itu seperti…seperti apa ya? Mmm…enggak bisa dikatakan.”
“Pestanya sendiri gimana?” Ajeng bertanya penasaran
“Ya menyenangkan juga. Aku merinding sih pas masuk gedung diiringi gamelan, melihat dekorasi yang indah, kamu yang cantik. Tadi sempat juga nyicip makanan enak dari katering pilihan ibumu!” Untung mendelik sambil tersenyum pada Ajeng yang menatapnya kesal karena katering pilihannya ditolak Ibu. “Tapi, tahu enggak, Jeng? Setelah ijab kabul, aku sudah teramat lega. Beneran! Andaikan ada yang berhalangan datang pun tidak apa-apa. Kalau ada yang kehabisan makanan juga aku enggak akan stress. Sudah takdir. Yang penting, kitanya sudah sah, lainnya terserah…” kata Untung.
“Iya, ya?” Ajeng memikirkan kalimat terakhir Untung.
Kedua pengantin baru itu sama-sama menatap langit-langit kamar.
Lama sekali mereka berniat untuk menikah, karena sudah yakin satu sama lain. Mereka pernah mengungkapkan kepada kedua orang tua masing-masing bahwa mereka hanya ingin menikah, tidak perlu pakai pesta. Namun, mereka kalah negosiasi dengan para orang tua, karena masih kuliah.
Setelah kuliah, masih harus bersabar lagi, menunggu keduanya atau setidaknya Untung bekerja. Takut dikata-katai Mau kasih makan apa? Memangnya kenyang makan cinta? Klise, sekaligus ada benarnya. Padahal, niat baik pasti dikasih jalan baik juga. Rezeki akan mengikuti. Namun, lulus kuliah menjadi semacam syarat lain untuk menikah.
“Ironis ya, Sayang. Kita menunggu sekian tahun untuk menikah. Padahal yang kita tunggu, sesungguhnya prosesi ijab kabul yang tadi berlangsung tidak sampai satu jam.”
“Iya. Semua syaratnya mudah. Manusianya yang mikir susah…” Untung tertawa kecil, sambil memejamkan mata.
Berdua, lalu membahas masa-masa ketika meminta izin kembali kepada orang tua masing-masing untuk diperbolehkan segera menikah. Sudah lulus kuliah, sudah mulai bekerja. Ternyata, mereka masih harus menghadapi tantangan lainnya: mengurusi resepsi pernikahan.
Disinilah tiga sudut pandang bersitegang. Impian Ajeng dan Untung, harapan orang tua Ajeng, dan harapan orang tua Untung. Masing-masing mempunyai paham dan bayangan tentang suasana resepsi pernikahan yang akan digelar. Bahkan tiga pihak memiliki daftar panjang nama tamu yang akan diundang. Tidak masalah, sih… Yang masalah? jumlah dananya.
Tabungan pernikahan Ajeng dan Untung jelas tidak cukup untuk mengundang semuanya. Terlebih lagi, mereka tidak ingin pernikahan yang sesak dengan orang-orang yang sesungguhnya hanya melintas dalam kehidupan mereka. Yang bertemu hanya beberapa tahun sekali, bahkan orang-orang yang dikenal namanya dari cerita, tanpa pernah tahu wujudnya.
Perlu resepsi untuk menghindari fitnah, menurut orang tua Ajeng dan Untung. Muncul beberapa opsi untuk didiskusikan pihak orang tua masing-masing, dengan Ajeng dan Untung sebagai penengah.
Oke, bagaimana kalau di rumah saja?
Tidak cukup menampung undangan, rumah kita kecil.
Bagaimana kalau ambil paket di hotel dengan budget tertentu biar praktis?Tapi kemungkinan jumlah tamu tidak bisa sebanyak yang diharapkan.
Sesuai anggaran, tapi jumlah tamu dipangkas? Mendingan di gedung biasa. Lebih banyak yang bisa diundang.
Tapi… tapi… tapi…
Ah! Buntu!
Usul resepsi sederhana di rumah sampai di hotel sekalipun, tidak menemukan titik tengah. Tidak bisa memangkas jumlah undangan, tapi tetap ingin megah. Usul nikah di KUA saja, atau nikah tamasya, apalagi. Ditolak mentah-mentah. Yang mau menikah kebingungan. Jadi, antara visi dan misi, serta harapan dan kenyataan, tidak ada yang tersambung. Seperti film kartun, tiba-tiba bermunculan visual dalam benak tentang konsep-konsep resepsi pernikahan impian dan angka-angka yang berseliweran. Budget!
Apakah ini semacam penolakan halus dari para orang tua atas hubungan mereka? Tidak juga. Restu sudah ada sejak dulu. Tidak ada masalah dengan cinta. Ini hanya masalah menemukan titik tengah, antara yang mau menikah dan yang menikahkan. Ini lebih susah daripada bikin skripsi sampai lulus sidang.
Sekali waktu, Ajeng dan Untung punya ide yang agak nyeleneh. Ajeng menyampaikan kepada ibundanya. Dimulai dengan pertanyaan untuk menarik pernyataan.
“Bu, resepsi itu untuk apa, tujuannya?”
“Ya… biar tidak timbul fitnah.”
“Sebagai pengumuman gitu kan, Bu?”
“Iya, biar banyak yang mendoakan.”
“Aku dan Untung ada ide, Bu. Bagaimana kalau kita buat kartu pemberitahuan saja. Dicetak seindah kartu undangan, namun sifatnya pemberitahuan, bukan undangan. Kita kirim dengan menyertakan souvenir. Simpel.”
Ibu mengerutkan dahi. Berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya.
“Ah… aneh! Nanti resepsinya gimana?”
“Ya keluarga terdekat aja, Bu. Kalau hanya keluarga terdekat bisa di hotel, atau sewa villa sambil liburan.”
“Ah, jangan Ajeng. Nanti enggak enak”
“Enggak enak sama siapa, Bu? Kan yang lain dikirim pemberitahuan berikut souvenir tadi. Tetap bisa minta doa restu, kan?”
“Ibu enggak enak mengkategorikan mana yang dekat dan yang tidak begitu dekat. Dunia itu sempit Jeng, semua saling kenal.”
“Ya, kita batasi saja sampai om, tante dan sepupu-sepupu Ajeng dan Untung Bu,”
“Nanti gimana sama calon mertua kakakmu? Itu sudah kenal dekat. Belum lagi tante-tante calon mertua kakakmu juga ibu sudah kenal. Terus, gimana dengan adik kakak dari kakek nenekmu? Itu juga dekat.”
“Yah! Ibu!… adik kakak dari nenek dan kakek itu pun sudah beranak pinak, Bu… gimana kita bisa nyetop batasannya?”
“Sudahlah Ajeng, nanti Ibu cari cara biar ada dananya. Berdoa saja.”
Buntu lagi.
Betul rupanya kata orang. Rencana pernikahan sering menimbulkan konflik.
“Bagaimana ini? keluarga adik dan kakak dari nenek, keluarga adik dan kakak dari kakek, pihak ibuku dan pihak ayahku. Lalu, dari pihak orang tuamu. Adik kakak calon mertuanya Mas Bimo, mau diundang juga. Kawan sekolah Ayah, Ibu aku. Kawan sekolah Ayah dan Ibumu. Sebagian besar dari mereka kita tidak tahu. Sekadar syukuran yang diadakan di rumah pun, Ibu kurang setuju karena rumah terlalu kecil.”
“Usul kirim pemberitahuan dan souvenir itu? Enggak diterima, ya?” tanya Untung
Ajeng menggelengkan kepala. Sebenarnya mereka berdua tidak mau pernikahan ini menjadi beban dan terhalangi. Ajeng dan Untung ingin pernikahan yang berkesan bagi mereka berdua. Ini sesungguhnya tentang mereka, bukan tentang orang-orang.
“Aku ngerti, Tung! beberapa pos tidak akan kupangkas. Perias, fotografer, dan katering, aku tetap ingin yang maksimal. Konsep pernikahan yang kita rencanakan juga. Tapi jumlah tamu?” Ajeng mulai histeris. Gelap mata, hingga enggan melihat dari sudut pandang lain. Untung mengusap punggung calon istrinya. Ajeng menarik napas terburu-buru, lalu lanjut berkata-kata lagi.
“Tamu-tamu jauh juga nanti ketemu sama kita hanya sekali dua kali seumur hidup kita kan? Memangnya foto dengan tamu yang tidak terlalu kita kenal, akan dipajang di rumah kita? Bahkan foto dengan paman dan tante kita saja belum tentu akan dipasang di dinding rumah kan? Coba! Pernah nggak nemuin rumah yang dindingnya banyak foto kawinan di pelaminan dengan tamu-tamu? Enggak! Paling juga foto keluarga inti saja! dengan orang tua, adik dan kakak. Sungguh enggak ngerti dengan keruwetan ini, Tung! Masa sih, gara-gara tamu kita enggak jadi nikah?”
“Hush, Ajeng, sabar… coba lihat dari sudut pandang orang tua kita. Berdoa saja, agar niat baik kita dilancarkan,” Untung menenangkan Ajeng.
***
Pada akhirnya, resepsi pernikahan impian orang tua Ajeng dan Untung terpenuhi. Entah bagaimana caranya, rezeki datang juga. Dapat potongan harga, bantuan profesional teman, hingga rezeki Ayah dan Ibu akhirnya bisa mengakomodir semuanya. Segala kepusingan, usulan dan harapan banyak orang, membuat Ajeng dan Untung mengalah di beberapa detail. Mereka berdua hanya berharap pada hal yang paling esensial dari pernikahan: Ada cinta, ada Tuhan, ada janji pada-Nya.
Susah sekali memang merubah kebiasaan. Manusia seakan dibatasi oleh standar dan norma-norma orang lain. Selalu lebih gelisah dengan “Apa kata orang nanti?”
Dari keinginan mereka tentang pesta yang santai, pada akhirnya Ajeng dan Untung rela pegal-pegal bersalaman dan tersenyum, entah pada siapa yang berbaris panjang menyalami. Berfoto dengan para tamu yang hasilnya hanya dilihat sebulan dua bulan atau setahun dua tahun, lalu disimpan dalam lemari.
Biarlah, mereka ikhlas. Yang penting, impian mereka untuk bersatu menjadi kenyataan.
***
Kedua pengantin baru itu masih memandangi langit-langit. Pengantin lelaki matanya terpejam, walau belum terlelap. Ia masih ingin mengobrol, namun kantuk dan lelah menyerang tanpa ampun.
“Tung?”
“Hmm?”
“Menurutmu, dua, tiga, lima tahun dari sekarang, apa yang akan tersisa dari resepsi yang penuh perjuangan hari ini?”
“Hmm… tidak banyak. Paling cincin kawin kita kalau masih muat, lalu surat nikah, dan foto kita berdua yang terpaku di dinding rumah. Selebihnya, kita akan mengurusi hal-hal yang lebih nyata. Cari rumah, bayar tagihan-tagihan bulanan. Lalu ada anak. Menjamin kehidupannya: makanan, kesehatan, kebahagiaan dan pendidikannya.”
“Ha…ha…ha… Ironis, ya. Dari resepsi tidak ada yang tersisa.”
“Ada, sih. Doa dari para tamu.” Suara Untung yang bijak, semakin pelan.
“Doa restu yang tadinya mau kita mohon lewat surat pemberitahuan bersama dengan souvenir itu. Iya, kan?”
“Hmm…Iya juga sih…”
“Tung, nanti kalau kita punya anak, pernikahannya gimana, ya? Pasti lebih simpel, kan?”
“Belum tentu. Kita kan belum pernah tahu rasanya jadi orang tua. Bisa jadi kita lebih ribet dari orang tua kita. Lagian, bikin anaknya aja belum, Jeng…” suara Untung sudah terdengar seperti gumaman yang nyaris tidak terdengar.
“Ha ha ha! Iya, ya?” Ajeng tertawa lagi.
Ajeng beranjak dari tempat tidur, berjalan mematikan lampu kamar mandi yang dari tadi masih ia biarkan menyala. Lalu mematikan lampu kamar pengantin mereka. Ajeng berbaring di tempat tidur, menghela napas, menghirup wangi melati di kamar itu. Ia bersiap memulai pernikahan yang sesungguhnya. Pernikahan seumur hidup.
“Untung…” Ajeng memanggil, seraya mengusap wajah suaminya.
Grook…grooook… Untung mendengkur. Suaminya tertidur kelelahan. Ajeng tertawa kecil. Ia juga mengantuk. Ternyata, malam pertama mereka juga tidak harus dilewati seperti cerita malam pertama pengantin lain. Tentunya, masih banyak waktu. Besok, lusa… oh, ya! seumur hidup!
Perempuan itu mencium pipi suaminya, lalu merebahkan kepala di dada lelaki itu sambil memeluknya. Dengkuran dan detak jantung Untung terdengar.
Ia setuju. Beberapa tahun lagi, mungkin hanya surat nikah, cincin kawin dan satu dua foto pernikahan di dinding saja yang akan tersisa dari semua yang bersifat materi dari resepsi hari ini.
Namun, dengkuran dan detak jantung ini yang akan ia dengar seumur hidup di telinganya. Melodi yang lebih indah dari lagu-lagu pada resepsi tadi. Dan janji mereka pada Tuhan adalah pernikahan yang sesungguhnya.
Hati Ajeng yang penuh syukur dan damai, justru kini tengah berpesta.
(2016)