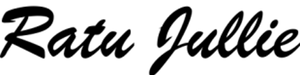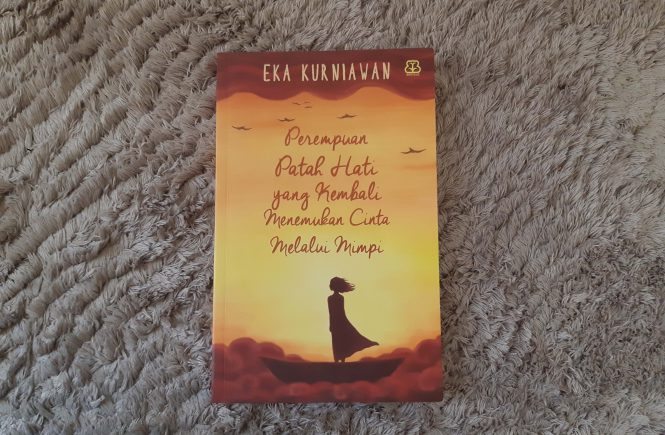Semua berawal dari sebuah pertanyaan saya kepada lelaki itu, di sekitar bulan Februari – Maret 2007.
“Kamu mau kado apa, buat April nanti?” tanya saya
“Semua tulisan kamu di lemari dibikin buku,” katanya.
Saya terkekeh. Tapi muka lelaki di hadapan saya serius. Lalu, kita mulai berdialog tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Saya ini banyak enggak ngeh-nya. Tentang belakang layar dunia kepenulisan, misalnya. Saya dulu itu semacam sebaliknya dari sifat FOMO, yang sekarang jadi gejala sosial LOL!. Ah… lebih sederhananya: pemalas dan merasa cukup jadi penikmat. Jadi, saya malah tidak banyak tahu dan tidak banyak cari tahu tentang sesuatu, kecuali sebuah situasi sudah di depan mata. Bahwa banyak buku yang diterbitkan secara indie, saya tidak ngeh apalagi berpikir bahwa itu juga bisa saya lakukan. Tunggu!! apakah saya mau menerbitkannya?
Atas nama hobi, saya mulai menulis sejak sekolah dasar. Puisi. Ya, puisi-puisi anak-anak yang bahkan kata saya juga tidak bagus-bagus amat. Di luar itu, saya suka sekali membaca. Saya suka juga pelajaran bahasa. Bahasa Indonesia di sekolah, juga bahasa Inggris di tempat les (dulu kan, mata pelajaran Bahasa Inggris baru didapatkan di SMP, sementara saya ikut les di luar sekolah, sejak SD).
Di sekolah dasar pula, saya punya sahabat pena pertama saya dari Jakarta, yang notabene keponakan ibu guru. Lalu, ditambah sahabat pena kedua dari Prabumulih, sahabat pena berikutnya dari Medan, dan seterusnya hingga saya SMA, dengan ambisi satu teman satu negara Ha ha ha! tentu tidak tercapai. Sensasi menyenangkan saat menerima surat dan segala hal yang berkaitan dengan pos, sama menyenangkannya dengan menulis suratnya. Tidak ada rasa bosan bercerita, tidak pula pegal menulis.
Begitulah, rangsangan menulis saya saat SD dulu. Berlanjut dengan menulis Diary, dan akhirnya mulailah menulis puisi-puisi di sebuah buku.
Apakah saya berniat menerbitkannya? Tidak pernah terpikir sedikit pun.
Kenapa? Apakah saya tidak percaya diri? Ah, enggak. Seingat saya, saya anak kecil yang cukup percaya diri.
(Bahkan ada cerita lain lagi seputar pertanyaan “Apakah tidak percaya diri” itu, di kemudian hari. Mungkin nanti akan saya tulis juga cerita tentangnya. Tapi, intinya sama sekali tidak pernah terpikirkan)
Jadi, tidak percaya diri? Bukan.
Bodoh? Nah, Iya kayaknya!
Lalai? Lebih tepat!
Saya pikir menulis itu hanya hobi. Sampingan saja. Dan zaman dulu itu, rasanya profesi penulis tidak pernah muncul dalam benak banyak orang, apalagi saya. Bodoh memang. Bukankah saya suka membaca? Nah, bukankah buku yang saya baca ada penulisnya?
Saya tidak pernah berpikir sampai ke situ. (Apalagi berpikir bahwa di kemudian hari, menulis itu punya dimensi yang lebih luas lagi dari menerbitkan buku. Menulis reportase, artikel, essay, skrip iklan, naskah drama sebuah event, skrip untuk videografi dan lain-lain)
Tanpa sadar, saya sudah mulai menjejali lemari kecil saya dengan Diary-diary juga buku puisi, dan melakukannya sebagai selingan dari rutinitas hidup yang “lebih penting dan normatif” lainnya: Sekolah, kursus, kuliah, bekerja dan menikah.
“Reuni” saya dengan dunia dunia baca dan tulis menulis justru meningkat lagi saat saya telah menikah dan tinggal di Aceh. Saya kerap membawa buku dari Bandung setiap kali ada kesempatan pulang, untuk di bawa ke Aceh. Dan mulai lagi menulis puisi dengan lebih intens.
Cerita flashback ini, bermuara ke pertanyaan saya pada suami tahun 2007, di paragraf awal tadi.
Lelaki yang dekat dengan saya sejak usia saya menjelang 19 tahun, tahu betul kesukaan saya. Selain puisi, saya kerap menulis pesan-pesan cinta buat dia. Sementara dia, adalah lelaki yang lebih romantis sikap dan verbalnya, daripada dalam tulisan. Dia penikmat tulisan-tulisan saya. Dan dia jauuuh lebih romantis bila tidak menulis. Ha ha ha ha…! Dia menulis hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan sajalah… lebih indah. LOL!
Nah, kembali ke jawaban dia, tentang kado untuk ulang tahunnya bulan April 2007. Dia ingin tulisan saya dalam lemari kecil itu keluar dan menjadi buku. Wacana itu bergulir. Walaupun saya mau mengabulkan, saya bilang padanya, bahwa saya tidak akan sanggup menjadikannya hadiah tepat di hari ulang tahunnya yang tinggal beberapa bulan lagi saja (jarak 1-2 bulan kalau gak salah). Tapi, saya berjanji untuk memenuhinya. Setelah itu barulah saya mulai proyek kecil saya itu. Membongkar folder puisi-puisi lama dan baru saya, menyusunnya, mengedit semampunya, dan membayangkan akan mengemasnya seperti apa. Saya juga mendatangi dua orang yang sekiranya berkenan memberi masukan tentang draft saya. Yang satu, penulis yang bermukim di Aceh. Satu lagi sahabat saya di Bandung. Keduanya memberi masukan positif. Itu yang terjadi selama beberapa bulan di tahun 2007. Lalu? Stuck!
Saya belum ketemu desainer yang pas untuk kover-nya. Dan, distraksi-distraksi hidup pun saya sambut dengan hangat, demi menghambat jalan terbitnya buku itu :p . Ceritanya, Alhamdulillah saya hamil di taun 2008 setelah 7 tahun penantian, namun sayangnya berakhir dengan keharusan dikuret. Larut dalam kesedihan, yang disambung distraksi-distraksi lainnya, saya mengendapkan lagi draft buku saya. Dosa dari mengingkari janji pada suami, tidak bikin saya cukup takut untuk segera membuat draft akhir. Meski demikian, saya tetap menulis puisi tambahan.
Saya lupa kapan tepatnya keinginan menyelesaikan buku itu muncul lagi. Yang pasti suatu hari di tahun 2009, saya ingat lagi, malu dan tidak enak hati. Utang pada suami tak kunjung terpenuhi. Dulu itu, saya tidak terpikir bahwa ada layanan printing buku satuan. Dulu itu, saya berpikir bahwa buku saya akan melalui jalan-jalan konvensional. Diproduksi dan dijual. Padahal, sekarang ini sudah berbagai macam layanan dan kemungkinan cara membuat buku non komersil. Bahkan sekarang secara digital pula.
Karena kekurangpintaran saya saat itu, saya panik sendiri. Kalau saya harus mencetak buku sebanyak 500 eksemplar, bagaimana distribusinya? siapa yang mau beli? Siapa saya?
Nah di sinilah, saya akui saya “sedikit” kurang percaya diri. Sedikit saja, karena keinginan itu tetap ada. Hanya saja saya perlu tahu apa buku tersebut layak? Apakah saya layak?
Untuk menjawab keraguan saya, akhirnya saya bernazar: Kalau ada satu saja karya saya diterbitkan oleh sebuah media cetak, maka saya akan meneruskan penerbitan buku indie saya.
“And when you want something, all The Universe conspires in helping you to achieve it” (The Alchemist, Paulo Coelho)
Mungkin begitulah semesta bekerja. Dalam waktu yang dekat dari nazar saya itu, seorang teman tetiba memberitahu saya bahwa Majalah Femina mengadakan sayembara Cerpen dan Cerbung. Saya pikir, coba saja deh.
Lagi-lagi: baru mau mencoba saja, keraguan muncul lagi. Syarat cerpennya: 6-8 halaman A4. Saya, belum pernah menulis sepanjang itu. Tulisan fiksi terpanjang saya adalah 4 halaman, dan terasa kurang baik. Tapi saya harus coba. Beberapa saat, saya jadi berkutat di sayembara cerpen ini. Dari pemunculan ide, mulai menulis, hingga menyunting. Alhamdulillah berhasil. Dua cerpen fiksi jadi juga. Karena setiap peserta boleh mengirimkan dua cerpen, saya bikin dua.
Pada dasarnya, saat itu saya sudah berhasil menang dari keraguan diri sendiri. Dari tidak bisa menjadi bisa. Bagus tidaknya, itu terserah juri. Saya sudah bahagia, telah sanggup membuat dua cerita pendek yang masing-masing memenuhi syarat untuk ikut serta. Saya mengirimkan keduanya, tanpa mengharap apa-apa.
Saat pemenang diumumkan beberapa bulan kemudian, saya sudah bisa membayangkan bahwa saya tidak akan menang. Tidak ada rasa kecewa, karena saya sudah bahagia di kata “menyelesaikan”. Namun, beberapa minggu setelahnya, kejutan datang.
Saya dikirim e-mail oleh redaksi, yang ingin mengkonfirmasi apakah cerpen “Dongeng yang Salah” belum pernah dipublikasikan? Karena rencananya akan dimuat dalam Majalah Femina beberapa edisi di depannya. Wow! Saya senang sekali. Benar-benar senang.
Majalah femina No. 8 (27 Februari – 8 Maret) 2010 memuat cerpen saya, “Dongeng yang Salah”. Sebuah cerita tentang perceraian dari sudut pandang anak. Saya ingat sekali, saat majalah tersebut terbit, saya tengah hamil 5-6 bulan. Bahagia berkali-kali lipat. Sampai sedikit vertigo. Lebay…
Setelah puas memandangi, lalu membaca ulang untuk tahu apa saja yang disunting oleh editor Femina (Alhamdulillah tidak banyak) untuk bahan evaluasi dan belajar, saya baru ngeh. Lho, saya nulis ini kan diiringi sebuah nazar? Bila ada satu saja karya saya dimuat di sebuah media, maka saya harus bersegera membayar janji saya pada suami. Maka, proyek “Pujangga Mumang” diteruskan, atas izin-Nya.
Jadi… yes! “Dongeng yang Salah”, punya kisah belakang layar yang sangat spesial, walau setiap karya tentunya spesial. Terima kasih pada redaktur majalah Femina, pada suami, pada sahabat-sahabat yang ada dalam “konspirasi semesta” untuk saya.


Setelah itu perjalanan saya berlanjut. Dan… seperti film yang beralur maju mundur, setiap flashback pada “film hidup” saya, kental sekali pesan dari semesta tentang kegiatan menulis. Pengalaman menulis untuk materi promosi klien, walau jabatan sebenarnya adalah account executive. Pengalaman seru yang panjang saat ikut seleksi reporter di sebuah majalah remaja (walau akhirnya tidak diterima). Menerima kerjaan lepas pertama berupa notulensi begitu lulus kuliah, berkorespondensi, Mencoba mengajar ekstrakurikuler menulis di sebuah Sekolah Dasar, dan “bau-bau” pena-kertas lainnya. Pada akhirnya, saya setuju pada sebuah tulisan….
“Tidak ada peristiwa yang betul-betul “kebetulan”. Atau dengan kata lain, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya” (Henry Manampiring, Filosofi Teras, halaman 41)
Hal ini juga, yang menjadi modal saya untuk mendampingi anak saya mengenali passion-nya. Karena, bukan tidak mungkin, yang dia lakukan dengan berbinar-binar saat ini adalah yang akan membuatnya bahagia seumur hidupnya nanti.
Happy 10th publishedversary dear “Dongeng yang Salah” It’s been a really incredible journey.
Februari /Maret 2010 – Februari/Maret 2020