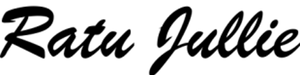Suatu siang, saat tengah menulis dan baterai laptop melemah, saya tergesa menuju colokan listrik terdekat, dengan tempat datar: Meja setrika. Lima langkah saja, sampai. Setelah save data, saya meninggalkan laptop yang lowbat itu. Menunggu sampai lampu indikatornya enggak “galak-galak” warna orange lagi. Saya slow, suami yang ketawa dan ribut manggil anaknya.
“Mahija, lihat deh, persis kayak di kover buku Ibu.”
Suami menunjuk meja setrika yang ditongkrongin laptop. Saya jadi balik lagi, untuk ikut melihat. Sebenernya siiih, enggak persis juga. Di kover enggak ada laptop-nya. Tapi dipikir-pikir ada apa antara saya dan meja setrika, ya?

Mungkin, ada Love-hate relationship gitu: benci tapi kudu. Gerah, tapi sering dapet ide.
Oh iya, masa karantina ini, saya memang lagi sering nongkrong di”posko” si Mbak ini, karena Mbak lagi Quarantine in The Time of Coronavirus (kayak judul film ya?). Nah, berhubung saya enggak betah terlalu lama nyetrika, jadi suka selang-seling dengan kegiatan menulis. Apalagi kalau ditunggu oleh baju-baju gede dan ribet, suka lebih ingin nulis,… langsung balik lagi deh ke meja makan yang 5 langkah itu. He he he… enggak segitunya, sih! Tapi aneh, menyetrika itu memang rada manjur buat mancing ide keluar lebih cepat. Entah kenapa.
.
Peristiwa beberapa siang yang lalu itu, membawa ingatan saya ke rangkaian proses pembuatan kover buku pertama saya. Setelah “dipaksa dengan manisnya” pada tahun 2007, akhirnya proses pembuatan buku dilanjutkan lagi sekitar bulan Maret-April tahun 2010. Mengendap lama, karena belum menemukan desain yang cocok untuk kovernya, dan seperti yang saya ceritakan selewat di kisah yang lalu, saya menempuh jalur nazar untuk membangun kekuatan. He he he…
Pernah menyerahkan draft Pujangga Mumang kepada seseorang untuk dibaca, dan diterjemahkan ke dalam desain visual. Masih belum pas. Sejujurnya, saya sendiri belum tahu apa yang saya mau. Selama mengendap 3 tahun, saya mencari tahu dan memastikan apa yang saya mau. Membaca ulang draft, sempat menambahkan beberapa puisi di dalamnya. Pelan-pelan terbayang, tapi masih belum jelas dan mengharapkan masukan.
Sesungguhnya, saya jatuh hati dengan kover buku Dee (Dewi Lestari), Rectoverso. Sepertinya, mimpi aja, kalau buku saya bisa didesain oleh orang yang sama. Tapi… kenapa tidak dicoba? Saya mencari tahu lokasi Kebun Angan, tempat sang desainer bernaung. Aaah, dekat! Saya hampir tidak percaya sedekat itu dengan lokasi saya tinggal (saat itu saya tinggal di rumah orang tua, dalam keadaan hamil). Saya hubungi team Kebun Angan, dan… responnya baik sekali!
Pertemuan pertama kali dengan perwakilan Kebun Angan untuk buku pertama saya yang judulnya Pujangga Mumang, terjadi juga. Saat itu sepertinya saya masih belum memberikan brief yang detail. Draft desain hasil briefing pertama dengan ilustrasi Masjid Raya Baiturrahman, saya terima. Saya memang menyampaikan bahwa proses kreatifnya terjadi di Aceh. Selebihnya, informasi bahwa Mumang artinya pusing atau lieur (dalam bahasa Sunda). Menyampaikan juga bahwa ide biasanya keluar saat saya sedang mengerjakan kerjaan rumah. Jadi, ketika saya mendapatkan Masjid Raya Baiturrahman di draft kover pertama itu, saya agak bingung dan sedikit geli.
Geli karena teringat pernah bekerja menjadi account executive (marketing) di sebuah studio desain grafis. Tugas saya, setelah mendapat klien adalah berusaha menangkap keinginan klien secara jelas dan menyampaikan ulang keinginan klien kepada desainer di kantor (jika desainer tidak ikut langsung bertemu klien). Iya, menjadi jembatan penghubung antara desainer dan klien. Saya ikut serta dalam brainstorming, membantu desainer “menerjemahkan” keinginan klien. Jadi, rasanya seperti mengulang cerita lama. Namun kali ini, sayalah kliennya. Yang terjadi mungkin kurang tertangkapnya maksud saya, karena: draft Pujangga Mumang tidak terbaca, atau justru saya yang “tidak terbaca”.
Pada brief kedua, saya lebih detail dalam mendeskripsikan bahwa tulisan-tulisan di dalam buku ini, merupakan kumpulan pemikiran sendiri, hingga cerita-cerita dari orang. Malah, ada sebuah puisi merupakan pesanan seorang kawan. Ini juga kumpulan pemikiran dan cerita yang diolah “dari rumah”. Jadi rasanya kurang pas kalau ilustrasinya Masjid Raya Baiturrahman, walaupun Aceh menjadi lokasi proses kreatifnya.
Desain selanjutnya sudah semakin dekat, maksud saya pun tertangkap. Kemunculan gambar meja setrikaan dan tempat tidur, menggambarkan betul bahwa saya suka disatroni “wangsit”, di rumah. Langit-langit kamar, suara jatuhnya air di ember, meja makan dengan penganan plus secangkir kopi, pakaian di jemuran, dan… meja setrika, tentu saja. Semua puisi di halaman dalam pun “dibingkai”. Akhirnya, Sebuah mock up, dari beberapa kali revisi, saya terima dan setujui.
.
Jadilah kover Pujangga Mumang seperti yang diterbitkan. Memuaskan (terima kasih Om Fahmi Ilmansyah), and I live happily ever after he he he… Sampai saat ini, Pujangga Mumang menjadi satu-satunya buku saya yang pernah mampir di Toko Buku Gramedia dan Toga Mas Bandung (2010-2011). Sungguh proses yang mengesankan dan memuaskan, membuahkan perkenalan.
Kalau dihitung-hitung, biaya produksi yang dihabiskan lumayan besar juga, apalagi jika dibandingkan saat ini dengan banyaknya pilihan paket penerbitan indie dan platform digital. Saya sudah mencoba self-publishing di tahun 2016, 2017 dan platform digital di tahun 2018. Dua pengalaman yang berbeda lagi.
Tapi, Pujangga Mumang adalah buku yang dilahirkan pertama dan terlama, yang terjauh dan berpeluh.
.
.
Akhir tahun 2020 ini, Pujangga Mumang akan memperingati 10 tahun kelahirannya. Should I celebrate? How?
*lari ke kamar setrika, cari ide lagiii…..